Paradoks Politik “Ikut Kiai”
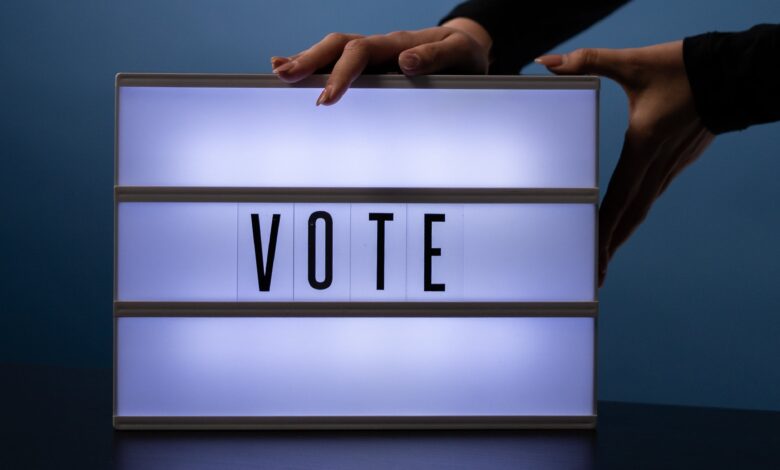
PERADABAN.ID – Di tengah kian mendekatnya pemilihan Capres-Cawapres 2024, Nahdlatul Ulama (NU) selalu dibanting ke dalam ring pertarungan. Padahal sudah beberapa kali, lini masa mengabarkan kalau NU tidak terlibat dalam politik praktis.
Saya memahami, tesis ini sangat klasik dan klise. Sejarah dan rentetan peristiwa politik Indonesia, terpaut dengan eksistensi NU.
Juga mutakhir, memang terdapat pengurus NU yang menjadi tim pemenangan salah dari kandidat atau bahkan menjadi kandidat itu sendiri di tingkat keragaman kontestasi.
Dalam fenomena ini, kedewasaan kader dalam berorganisasi diuji integritasnya. Organisasi diuji netralitasnya.
Makanya, bagi NU secara organisasi telah menutur regulasi yang perlu dijalankan anggotanya. Ada yang cuti dan seterusnya. Semata, aturan ini untuk menjaga martabat organisasi sebagai optimalisasi peran keagaamaan dan kemasyarakatan.
Kebebasan berpolitik bagi warga NU dibuka selebar-lebarnya asalkan dia mengikuti aturan main. Ini mencerminkan realitas organisasi yang berdiri 1926 itu pada keputusan fundamental yang kita kenal sebagai khitah 1926.
Baca juga:
Pada periode ini, tidak ada hubungan istimewa NU dengan partai politik. Sejak menjadi partai politik pada 1952 – setelah menarik diri dari Masyumi – lalu dipaksa bergabung dengan PPP, NU menarik diri dari politik praktis.
Tidak adanya hubungan intim, tidak spesial dan ekslusif antara NU dan PPP mengantarkan pada kebijakan yang membebaskan anggotanya untuk memilih dan aktif di partai apapun dengan catatan, tidak diperbolehkan menduduki jabatan di pimpinan partai dan NU secara bersamaan.
Legitimasi sejarah dan regulasi pada hakikatnya, tidak pernah berjarak dari kepemimpinan moral NU terhadap titah kiai sepuh. Keberadaannya selalu menjadi penanda terjalinnya ruang takdzim kepada mereka yang berwawasan keilmuan tinggi dan mulia secara spiritual.
Dan dalam banyak kesempatan, Syuriyah sebagai pimpinan tertinggi di tubuh NU, pasti menjadi acuan pijakan bagi keputusan-keputusan yang diambil jajaran Tanfidziyah. Termasuk di dalamnya, adalah dinamika internal organisasi di Jawa Timur.
Tapi apalah daya, nalar berorganisasi dilumat mentah-mentah oleh eksistensi pendengung yang melulu mengidentifikasi gestur politiknya dengan “ikut kiai”.
Redaksi itu menjadi alat jitu untuk memelintir peristiwa administratif ke dalam kepentingan politik yang memalukan. Bahasa dan kekuasaan, diraut untuk memoles figura kepentingannya sedemikian rupa. Seolah-olah, mereka lagi ketiban zalim, alih-alih buta aturan.
Menjelang penutup tahun, laman berita online memberitakan, salah seorang Paslon mengatakan tentang gaya keotoriteran organisasi yang main copot dan pecat. Menariknya, Paslon ini setaliikat dengan pendengung yang melulu menghardik kebijakan-kebijakan NU yang tidak menguntungkannya.
“Itu menular, bapak ibu sekarang perhatikan, ketika ada keputusan-keputusan yang tidak mengikuti proses nanti turun. Ormas pun bisa begitu kemudian, mecat-mecat. Kejadian kan ada pemecatan-pemecatan kemarin. Pakai prosedur tidak? Kenapa dibiarkan? Itu yang namanya menular,” demikian ucap Paslon Nomor Urut 1 dikutip dari detik.com, 31/12/2023.
Baca juga:
- Malam Peringatan HAB Ke-78 Kemenag RI, Gus Mus dan Sejumlah Sastrawan Bacakan Doa dan Puisi untuk Palestina
- Puisi Gus Mus Menggelegar di Malam HAB Ke-78 Kemenag
Seperti pada biasanya, narasi Anies selalu manis. Pembukanya digincu sedemikian apiknya. Bahasanya tertata kata demi kata. Gesturnya mengorkestrasi maksudnya. Mau benar atau tidak, itu urusan belakang.
Asalkan, pesan yang disampaikan itu menyentuh katup telinga audiensnya. Dengan mengelemnya – bukan menggunakan aibon – melalui raut ketakutan, kekhawatiran dan hal pikat lainnya, yang seolah-olah menggambarkan kesamaan nasib.
Betul, ada penyakit sosial yang menular. Bukan tentang contoh yang disampaikan seperti penyakit sosial yang menular. Tetapi pola yang dilakukan antara Anda sebagai kandidat dan pendengungnya dalam mengaktivasi kepentingan dengan cara-cara membangun sentimen kepada yang lain yang tidak seiya dan mengiyakan.
Mulai dari mufaraqah, atau seperti hal di atas yang diucapkan, lalu sebelumnya: sunnatullah hujan jatuh ke bumi pada tahun Pilkada DKI Jakarta beberapa tahun silam. Bukankah deretan yang naif jika itu tidak diakui sebagai watak politik yang lamis?
Pendengung, memang ditugaskan bukan untuk mendedah kesaksian atas peristiwa dengan objektif. Pendengung diciptakan untuk memuja-muja tuannya. Dan itu sekarang, masif atas nama “ikut kiai”. Besok, apa lagi?




One Comment